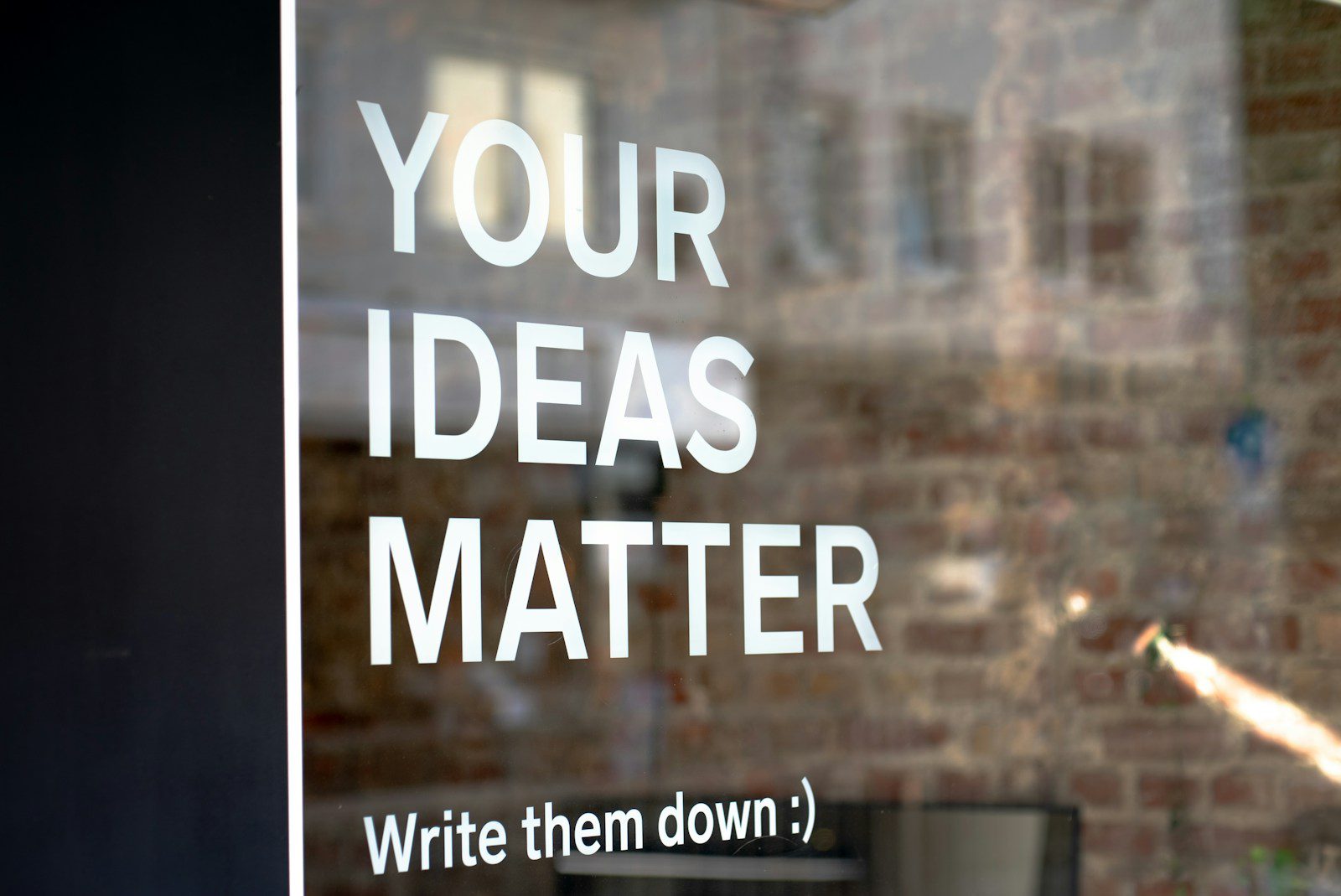Abolisi dan Amnesti di Indonesia: Jalan Keadilan atau Instrumen Politik Kekuasaan?
Oleh: Aditya Irawan
Junior Associate TTW & Co.
A. Pendahuluan
Bayangkan sebuah kasus besar yang menyita perhatian publik. Proses penyidikan telah berjalan, sorotan media begitu tajam, tetapi tiba-tiba Presiden mengeluarkan keputusan: proses hukum dihentikan. Pertanyaan pun muncul—apakah ini demi tegaknya keadilan substantif, atau justru ada kepentingan politik yang sedang dimainkan?
Inilah dilema yang selalu muncul ketika membicarakan amnesti dan abolisi. Dua kewenangan konstitusional Presiden yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, di mana Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Keduanya bersifat ekstra-yudisial karena tidak lahir dari putusan pengadilan, melainkan dari keputusan eksekutif.
Amnesti berarti penghapusan seluruh akibat hukum pidana dari suatu tindak pidana tertentu, baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan. Sedangkan abolisi merupakan penghentian proses hukum pada tahap penyidikan, penyelidikan, atau persidangan. Dalam praktiknya, keduanya sering digunakan bukan hanya untuk tujuan hukum, melainkan juga untuk pertimbangan politik dan rekonsiliasi nasional.
Pertanyaannya: apakah amnesti dan abolisi benar-benar jalan keadilan, atau justru instrumen politik untuk melindungi kepentingan tertentu?
B. Dasar Hukum dan Perbedaan Konseptual
Pasal 14 UUD 1945 secara eksplisit menegaskan:
Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Secara normatif:
Amnesti adalah penghapusan akibat hukum pidana, biasanya diberikan dalam konteks politik, konflik nasional, atau untuk mengoreksi penegakan hukum yang keliru.
Abolisi adalah penghentian proses hukum terhadap perkara yang sedang berjalan, dan umumnya diberikan dalam kasus yang dianggap sensitif secara politik.
Perbedaan mendasar keduanya:
| Aspek | Amnesti | Abolisi |
|---|---|---|
| Objek | Akibat hukum pidana | Proses hukum yang sedang berjalan |
| Tahap | Bisa sebelum/sesudah putusan | Hanya sebelum putusan pengadilan |
| Tujuan | Rekonsiliasi politik/humaniter | Menghentikan perkara sensitif |
| Pertimbangan | Harus dengan persetujuan DPR | Harus dengan persetujuan DPR |
C. Implikasi Hukum dan Politik
Secara hukum, pemberian amnesti atau abolisi berarti menghentikan jalannya penegakan hukum pidana. Hal ini menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip equality before the law. Dalam konteks tertentu, pemberian amnesti/abolisi dapat dipandang sebagai koreksi atas kekeliruan hukum (contoh: amnesti untuk Baiq Nuril), atau sebagai langkah rekonsiliatif (contoh: amnesti bagi mantan kombatan GAM).
Namun, dalam konteks politik, kewenangan ini dapat menimbulkan kecurigaan. Publik bisa saja melihatnya sebagai alat impunitas yang melindungi elite politik. Jika hanya kelompok tertentu yang mendapat perlakuan istimewa, kepercayaan terhadap sistem hukum akan runtuh.
Isu ini menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan dinamika politik mutakhir. Kasus Hasto Kristiyanto dan polemik yang menyeret nama Harun Masiku menimbulkan pertanyaan publik: apakah ada kemungkinan kekuasaan eksekutif menggunakan instrumen abolisi untuk melindungi aktor politik tertentu? Jika hal itu terjadi, maka pemberian abolisi bukan lagi instrumen keadilan, melainkan bentuk intervensi politik yang mengikis legitimasi hukum.
Begitu pula dengan kasus Tom yang ramai diperbincangkan. Kontroversi hukum ini menunjukkan bagaimana praktik penegakan hukum di Indonesia tidak pernah steril dari tarik-menarik kepentingan politik. Seandainya Presiden menggunakan hak abolisi atau amnesti dalam perkara seperti ini, publik akan sulit mempercayai bahwa keputusan tersebut benar-benar demi kepentingan hukum dan keadilan.
Dengan demikian, implikasi hukum dari amnesti dan abolisi tidak bisa dilepaskan dari implikasi politiknya. Instrumen ini bisa menjadi jembatan rekonsiliasi nasional, tetapi juga bisa menjadi alat kekuasaan jika tidak dikontrol dengan baik.
D. Penutup
Amnesti dan abolisi adalah pengecualian dalam sistem hukum pidana Indonesia. Keduanya bersifat ekstra-yudisial, dijalankan melalui keputusan Presiden dengan pertimbangan DPR. Di satu sisi, instrumen ini dapat menjadi alat korektif terhadap ketidakadilan hukum formal, serta menjadi sarana rekonsiliasi dalam situasi konflik. Namun, di sisi lain, kewenangan ini juga rawan disalahgunakan untuk melindungi kepentingan politik tertentu.
Dalam konteks demokrasi Indonesia yang masih berproses, transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian amnesti atau abolisi menjadi hal yang mutlak. Tanpa itu, publik akan memandang keputusan Presiden bukan sebagai wujud keadilan, melainkan sebagai permainan politik kekuasaan.
Pada akhirnya, legitimasi amnesti dan abolisi tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum, tetapi juga oleh kepercayaan publik. Presiden, DPR, dan seluruh institusi negara harus menyadari bahwa setiap keputusan dalam ranah ini adalah ujian moral dan politik, bukan sekadar kebijakan hukum.