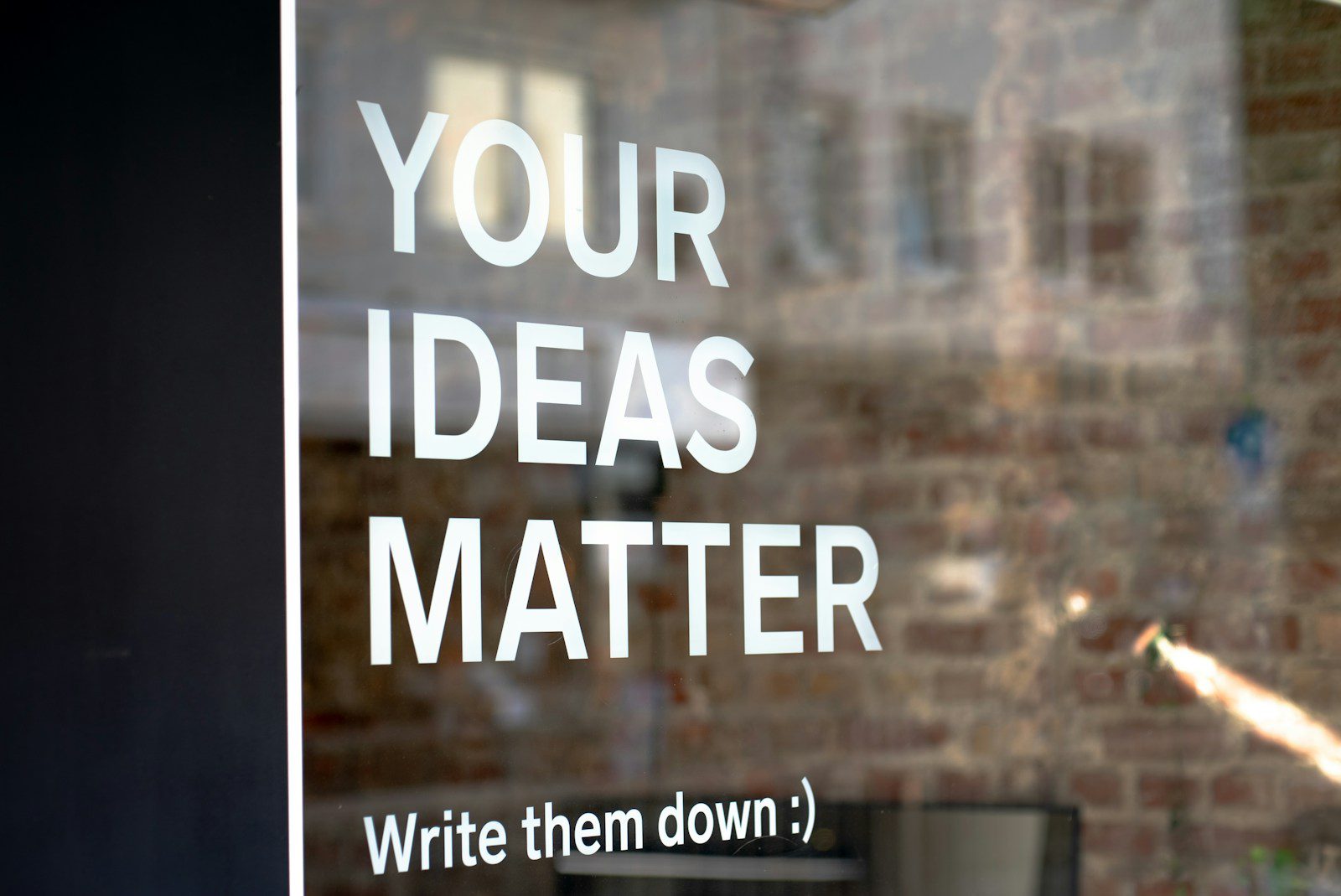Oleh: Lutfi Vander Suwarsa
Junior Associate Kantor Hukum Tarmizi Tahir Wagola
A. Pendahuluan
Abolisi dan amnesti merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang bersifat khusus karena tidak melalui mekanisme pengadilan, melainkan dijalankan berdasarkan keputusan Presiden. Hal ini menjadikan keduanya sebagai bentuk diskresi eksekutif yang dilegalkan oleh konstitusi. Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), ditegaskan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) . Oleh karena itu, meskipun bersifat prerogatif, pelaksanaannya tidak bersifat absolut karena tetap harus mendapatkan legitimasi politik dari lembaga legislatif.
Perbedaan paling mendasar antara amnesti dan abolisi terletak pada objek dan waktu pemberiannya. Amnesti diberikan untuk menghapus seluruh akibat hukum dari suatu tindak pidana tertentu, baik sebelum maupun sesudah adanya putusan pengadilan, dan umumnya diberikan dalam konteks politik seperti konflik atau pemberontakan. Sementara itu, abolisi hanya diberikan pada tahap pra-adjudikasi, yaitu saat perkara sedang dalam proses penyidikan, penyelidikan, atau persidangan, dan bertujuan untuk menghentikan proses hukum yang sedang berjalan . Dalam praktiknya, abolisi seringkali digunakan untuk mengakhiri perkara-perkara yang secara hukum dianggap sensitif atau berpotensi menimbulkan instabilitas.
Pemberian amnesti dan abolisi tidak hanya berimplikasi hukum, tetapi juga berdampak secara sosiopolitik. Dalam beberapa kasus, seperti amnesti kepada mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan amnesti kepada Baiq Nuril, tindakan Presiden ini dinilai sebagai upaya untuk mengembalikan rasa keadilan sosial serta menciptakan rekonsiliasi nasional . Namun, pada sisi lain, pemberian kewenangan semacam ini juga dapat disalahgunakan untuk melindungi kelompok tertentu dari jeratan hukum atau untuk kepentingan kekuasaan, sehingga menimbulkan kritik publik.
Dari sudut pandang yuridis, keberadaan amnesti dan abolisi menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui adanya fleksibilitas dalam penegakan hukum, terutama ketika prinsip-prinsip keadilan substantif dianggap lebih penting daripada hukum formal. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa tindakan ini tidak boleh dilakukan secara serampangan atau tanpa dasar pertimbangan hukum dan etika yang kuat. Keterlibatan DPR dalam proses ini menjadi mekanisme check and balance agar kekuasaan eksekutif tidak berjalan secara otoriter .
Dengan demikian, abolisi dan amnesti harus dipandang sebagai alat korektif dan rekonsiliatif dalam sistem hukum nasional yang digunakan secara hati-hati, proporsional, dan akuntabel. Keduanya berperan dalam menjembatani kepentingan hukum dan politik, serta menjadi indikator kedewasaan demokrasi suatu negara. Dalam praktiknya, tantangan terbesar terletak pada bagaimana menjaga kewenangan ini tetap berada dalam koridor konstitusional dan tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan hukum yang hakiki
B. Pengertian dan Dasar Hukum
Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara eksplisit menyebutkan bahwa:
a. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
b. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .
Secara normative :
a. Amnesti adalah penghapusan akibat hukum pidana terhadap suatu perbuatan pidana tertentu, baik terhadap orang yang sudah dijatuhi pidana maupun yang belum diperiksa atau diadili. Biasanya diberikan dalam konteks politik atau konflik nasional .
b. Abolisi adalah penghentian proses hukum pidana terhadap seseorang atau kelompok orang yang sedang diperiksa, disidik, atau diadili .
Keduanya merupakan tindakan hukum yang bersifat ekstra-yudisial, karena lahir dari kewenangan eksekutif (Presiden), bukan putusan pengadilan. Hal ini menjadikan abolisi dan amnesti sebagai alat konstitusional yang unik karena beroperasi di luar mekanisme peradilan, namun memiliki dampak langsung terhadap proses hukum pidana.
Meskipun tidak diatur secara rinci dalam undang-undang tersendiri, pemaknaan abolisi dan amnesti berkembang melalui praktik ketatanegaraan serta yurisprudensi. Beberapa pakar hukum tata negara berpendapat bahwa pemberian amnesti atau abolisi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Presiden karena memerlukan legitimasi politik dari DPR. Kewajiban memperoleh pertimbangan DPR ini merupakan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan Presiden agar tidak bersifat otoriter .
Dalam konteks hukum pidana, amnesti dan abolisi dapat digolongkan sebagai alasan penghapus penuntutan (negatief vervolgingsmonopolie), karena keduanya mengakibatkan tidak dilanjutkannya proses hukum oleh aparat penegak hukum. Namun, berbeda dengan deponering oleh Jaksa Agung yang bersifat administratif, amnesti dan abolisi memiliki kekuatan hukum yang bersumber dari konstitusi dan memiliki cakupan yang lebih luas secara nasional .
Contoh konkret dari penggunaan kewenangan ini adalah pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun, yang sempat divonis bersalah berdasarkan Undang-Undang ITE karena menyebarkan rekaman pelecehan verbal yang dialaminya. Presiden Joko Widodo mengusulkan amnesti tersebut kepada DPR, dan setelah disetujui, seluruh akibat hukum pidana atas perbuatan Baiq Nuril dihapuskan . Kasus ini menegaskan bahwa amnesti juga dapat digunakan dalam konteks koreksi atas penegakan hukum yang keliru, tidak hanya terbatas pada situasi konflik politik.
Secara historis, amnesti dan abolisi telah digunakan dalam berbagai momen penting dalam sejarah Indonesia, seperti pada masa transisi kekuasaan dan konflik daerah. Presiden Soekarno, misalnya, pernah memberikan amnesti kepada pelaku pemberontakan PRRI/Permesta. Demikian pula Presiden Habibie memberikan abolisi kepada beberapa tokoh yang dianggap sebagai tahanan politik Timor Timur . Penggunaan ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya bersifat yuridis, nilai-nilai rekonsiliasi, stabilitas nasional, dan kemanusiaan turut menjadi dasar pertimbangannya.
Perbedaan Abolisi dan Amnesti
Aspek Amnesti Abolisi
Obyek Akibat hukum pidana dari suatu perbuatan Proses hukum pidana yang sedang berjalan
Tahap Bisa diberikan sebelum atau sesudah putusan Hanya diberikan sebelum putusan pengadilan
Tujuan Umumnya untuk kepentingan politik rekonsiliatif Untuk menghentikan proses hukum tertentu
Pertimbangan Harus dengan persetujuan DPR Harus dengan persetujuan DPR
Contoh historis Amnesti Tap MPRS No. 11/1966 kepada Soekarno Abolisi oleh Presiden Habibie dalam kasus aktivis Timtim
C. Implikasi Hukum dan Politik
Pemberian amnesti dan abolisi seringkali menimbulkan kontroversi, terutama ketika dipersepsikan sebagai bentuk intervensi kekuasaan terhadap proses hukum. Dalam praktiknya, tindakan ini bisa menjadi alat rekonsiliasi (seperti dalam kasus GAM dan Papua), namun juga berisiko merusak kepercayaan terhadap supremasi hukum apabila tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Presiden sebagai kepala negara harus memastikan bahwa pemberian amnesti atau abolisi dilakukan dengan alasan yang kuat, berdasarkan pertimbangan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan bagi korban. Selain itu, keterlibatan DPR sebagai pemberi pertimbangan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 bukan hanya prosedural, tetapi menjadi penyeimbang politik yang penting agar tidak terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif .
Dari sisi hukum, pemberian amnesti dan abolisi berdampak langsung terhadap penghentian penegakan hukum pidana. Ini berarti bahwa dalam situasi tertentu, proses peradilan dapat dihentikan bukan karena alasan hukum murni, tetapi karena pertimbangan politik atau sosial. Hal ini tentu menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip equality before the law, sebab bisa terjadi ketidakadilan jika hanya kelompok tertentu yang mendapat perlakuan istimewa melalui amnesti atau abolisi . Oleh karena itu, penting agar pemberian fasilitas ini tidak mencederai asas non-diskriminasi dan tetap menjunjung nilai keadilan substantif.
Implikasi politik dari amnesti dan abolisi juga sangat signifikan, khususnya dalam konteks konsolidasi demokrasi. Misalnya, pemberian amnesti terhadap mantan anggota GAM di Aceh turut membantu memperkuat otonomi daerah dan meredam konflik bersenjata yang telah berlangsung lama . Di sisi lain, jika digunakan secara tidak tepat, tindakan serupa bisa menjadi alat impunitas yang menyuburkan budaya kekebalan hukum, seperti pada kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang tidak pernah sampai ke pengadilan karena adanya tekanan politik untuk penghentian proses hukum .
Perlu digarisbawahi bahwa kepercayaan publik terhadap hukum sangat tergantung pada konsistensi negara dalam menerapkan prinsip keadilan. Jika masyarakat melihat bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, maka legitimasi institusi hukum bisa runtuh. Oleh karena itu, setiap pemberian amnesti dan abolisi perlu didasarkan pada kajian komprehensif, disertai pertanggungjawaban moral dan hukum kepada publik. Mekanisme pelibatan masyarakat sipil serta evaluasi terhadap dampaknya menjadi sangat penting dalam menjaga kredibilitas tindakan tersebut .
D. Penutup
Abolisi dan amnesti merupakan pengecualian dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mengandung karakteristik ekstra-yudisial. Keduanya tidak dijalankan melalui proses pengadilan, tetapi bersumber dari keputusan Presiden dengan persetujuan DPR. Meski secara normatif diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, pelaksanaan kewenangan ini tetap menuntut kehati-hatian karena menyangkut prinsip dasar negara hukum dan demokrasi.
Dalam praktiknya, amnesti dan abolisi telah berperan penting sebagai sarana menyelesaikan konflik horizontal, mengoreksi ketimpangan hukum, serta memfasilitasi rekonsiliasi nasional. Contoh konkret seperti amnesti untuk GAM dan Baiq Nuril membuktikan bahwa kewenangan ini bisa menjadi alat pemulihan keadilan substantif, terutama ketika sistem hukum formal tidak mampu menjawab rasa keadilan publik.
Namun, penggunaan kewenangan tersebut juga menyimpan potensi penyalahgunaan. Jika tidak dikendalikan secara transparan dan akuntabel, amnesti dan abolisi bisa disalahartikan sebagai alat politik untuk melindungi elite dari jerat hukum. Oleh karena itu, penting bagi publik, akademisi, dan praktisi hukum untuk terus mengawasi bagaimana diskresi konstitusional ini diterapkan.
Secara politis, pemberian amnesti dan abolisi menjadi cermin kedewasaan demokrasi sebuah negara. Dalam negara yang sedang membangun konsolidasi demokrasi seperti Indonesia, mekanisme ini perlu ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang baik (good governance), tidak hanya sebagai kebijakan politik reaktif, tetapi sebagai strategi hukum yang dirancang berdasarkan analisis menyeluruh terhadap dampak hukum, sosial, dan psikologis.
Keterlibatan DPR dalam memberikan pertimbangan bukan hanya bentuk prosedural, tetapi bagian dari sistem check and balance yang harus ditegakkan. Legitimasi politik dari DPR mencerminkan suara rakyat, sementara keputusan Presiden harus mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan nasional jangka panjang. Maka dari itu, sinkronisasi antara hukum dan politik adalah kunci keberhasilan instrumen ini.
Sebagai junior associate di dunia praktik hukum, saya meyakini bahwa pemahaman mendalam terhadap abolisi dan amnesti akan memperkuat cara pandang kita terhadap konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia. Lebih dari sekadar alat pemutusan proses hukum, amnesti dan abolisi mencerminkan wajah kemanusiaan dari kekuasaan negara—yang seyogianya tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kemaslahatan rakyat dan martabat bangsa.
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tap MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno dan Pemberian Amnesti serta Abolisi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Buku
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2009.
Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya. Jakarta: Politeia, 1996.
Artikel Ilmiah/Jurnal
Bhakti, Ikrar Nusa. “Menyelesaikan Konflik Aceh: Antara Militer dan Sipil.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 6, No. 2, 2003.
Laporan Resmi/Kelembagaan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Laporan Tahunan 1999. Jakarta: Komnas HAM RI.
Sumber Daring/Media Massa
Tempo.co. “Amnesti Baiq Nuril Disetujui DPR,” 30 Juli 2019. Diakses dari: https://nasional.tempo.co/read/1230736/amnesti-baiq-nuril-disetujui-dpr

Abolisi dan Amnesti di Indonesia: Jalan Keadilan atau Instrumen Politik Kekuasaan?
Baca Selanjutnya
Abolisi dan Amnesti di Indonesia: Jalan Keadilan atau Instrumen Politik Kekuasaan? Oleh: Aditya IrawanJunior Associate TTW & Co. A. Pendahuluan